Pelemahan Rupiah, Kenaikan BI Rate, dan IHSG
Salah satu hotnews di pasar akhir-akhir ini adalah terkait
pelemahan Rupiah terhadap US Dollar, dimana hingga ketika artikel ini ditulis,
Rupiah sudah berada di level Rp14,326, melemah cukup signifikan dibanding
setahunan lalu yang masih di level Rp13,400-an, dan wajar jika orang kemudian
jadi khawatir: Bagaimana jika Rupiah terus saja melemah sampai katakanlah
tembus Rp15,000? Apakah kita akan mengalami krisis? Lalu bagaimana nasib pasar
saham?
Nah, meski mungkin soal Rupiah ini tampak buruk karena terjadi bersamaan dengan periode bear
market, tapi bisa penulis katakan bahwa there is nothing to worry about, at least until today, dan berikut penjelasannya.
Pertama, seperti
yang pernah saya tulis dulu (tapi lupa di artikel mana), jika Indonesia adalah perusahaan,
maka kurs Rupiah itu adalah ‘harga sahamnya’, dimana jika kinerja fundamental makroekonomi
nasional lagi bagus maka Rupiah akan menguat, sementara jika ekonomi lagi
lesu/krisis, maka Rupiah akan melemah. Namun demikian penulis sendiri
belakangan menyadari bahwa, jika Rupiah itu adalah seperti harga saham ‘PT Republik
Indonesia Tbk’, lalu kenapa kurs Rupiah sampai sekarang tidak pernah menguat
sampai ke level sebelum krisis moneter 1998 (Rp2,500-an per USD), padahal
ekonomi kita dalam dua dekade terakhir pasca krismon terbilang tumbuh pesat??
Dan jawabannya
adalah, karena tingkat inflasi di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi
di dunia, jauh diatas inflasi di negara-negara lain manapun, dan mungkin hanya
lebih baik dibanding negara-negara Afrika. Sebagaimana yang kita ketahui, inflasi menurunkan nilai mata uang. Dan
level inflasi kita yang mencapai 10% per tahun (rata-rata dari tahun 1997
sampai 2018) itu jauh lebih besar, dibanding inflasi Amerika Serikat (AS) yang
hanya 2 – 3% per tahun. Inilah kenapa Rupiah, meski pada waktu-waktu tertentu
menguat terhadap USD, tapi dalam jangka
panjang dia akan terus melemah terhadap USD. Jika anda lihat lagi sejarah kurs Rupiah di wikipedia,
maka akan kelihatan bahwa Rupiah sejak tahun 1970-an sampai sekarang selalu
melemah terhadap USD, tapi disini penulis akan tampilkan ringkasannya saja.
Tahun
|
Kurs
|
1966
|
250
|
1970
|
378
|
1980
|
626
|
1990
|
1,842
|
1998
|
14,800
|
2000
|
9,725
|
2010
|
9,036
|
2015
|
14,000
|
Jul-18
|
14,300
|
Nah, jadi jangan kaget
jika katakanlah pada tahun 2030 nanti, kurs Rupiah mungkin akan sudah jauh
lebih rendah lagi dibanding sekarang, dan itu sesuatu yang normal/bukan karena krisis ekonomi atau semacamnya. Proyeksi ini baru bisa berubah jika
inflasi di Indonesia, yang sekarang ini relatif rendah di level 3 – 4% per
tahun, bisa bertahan untuk seterusnya, tapi itu akan sulit untuk terjadi karena
sejak awal, geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan menyebabkan proses
distribusi barang membutuhkan biaya tinggi, sehingga harga sembako di Papua bisa
belasan kali lebih mahal dibanding di Jawa, dan itulah yang memicu terjadinya inflasi
selama ini. Beruntung, karena sekarang ini pulau-pulau di Indonesia mulai
terkoneksi dengan baik (dulu anda kalo mau ke Papua mungkin harus pake kapal laut,
tapi sekarang bisa pake pesawat, dan biayanya relatif murah dibanding dulu) maka
itu turut menurunkan biaya distribusi barang sekaligus menekan inflasi, tapi penulis
masih belum tahu apakah trend positif akan bertahan untuk seterusnya atau
tidak karena, actually, keadaan geografis Indonesia yang kita bahas diatas hanyalah satu dari sekian banyak faktor pemicu inflasi, sementara faktor-faktor lainnya bisa dibaca disini. Hanya saja, berbeda dengan faktor-faktor lainnya yang kadang terjadi kadang tidak, alias hanya berpengaruh dalam jangka pendek, maka kondisi geografis merupakan faktor konstan yang tidak akan pernah bisa berubah, dimana jarak antar pulau di Indonesia tidak akan menjadi lebih dekat ataupun lebih jauh. Jadi dalam kaitannya dengan turunnya kurs Rupiah dalam jangka panjang yang disebabkan inflasi, maka penulis menyebutkan faktor geografis ini sebagai penyebab jangka panjang inflasi tersebut.
Kedua, meski dalam
jangka panjang Rupiah akan terus turun terhadap USD, namun pada waktu-waktu
tertentu dimana ekonomi kita lagi ada problem alias krisis, maka penurunan itu akan lebih lebih tajam
dibanding biasanya (termasuk angka inflasi akan lebih besar dibanding biasanya, contohnya di tahun 1998 dimana inflasi mencapai 70%). Yup, jadi teori penulis diatas bahwa kurs Rupiah merupakan ‘harga
saham’ Indonesia, alias cerminan dari fundamental makroekonomi Indonesia, itu
tetap berlaku. Pada tahun 1997 – 1998, Rupiah anjlok dari Rp2,500 hingga sempat
menyentuh Rp18,000, sebelum kemudian menguat kembali dan stabil di 9,000-an.
Tahun 2008, Rupiah melemah ke 12,000-an karena imbas krisis global, lalu
menguat lagi hingga sempat dibawah 9,000 pada tahun 2011 (karena ekonomi
nasional yang lagi bagus-bagusnya ketika itu, thanks to booming komoditas), sebelum
kemudian turun lagi pelan-pelan seiring dengan economic slowdown hingga sempat
tembus Rp15,000 pada tahun 2015. Ini artinya dalam kurun waktu kurang dari 5
tahun, pelemahan Rupiah mencapai 60% (dari 9,000-an ke 15,000-an). Beruntung, pada
tahun 2016 harga komoditas mulai pulih, ekonomi mulai jalan lagi (meski
belum sekencang tahun 2011), dan alhasil Rupiah kembali menguat sebelum
kemudian stabil di Rp13,000-an, dan untungnya sampai saat ini, seperti yang sudah
penulis
sampaikan disini, ekonomi kita secara umum masih baik-baik saja.
Tapi Pak Teguh,
kalau dikatakan bahwa ekonomi masih aman, maka kenapa sekarang Rupiah melemah
lagi? Sebelum kita membahas soal itu, biar penulis bertanya satu hal: Pernah
nggak anda megang saham tertentu yang bagus dan valuasinya masih murah, dan itu
perusahaan masih aman-aman saja/gak ada masalah serius atau sentimen negatif apapun,
tapi harganya tiba-tiba turun sendiri? Well, pasti pernah bukan? Dan dalam
kondisi bear market seperti enam bulan terakhir ini, maka saham apapun
yang anda pegang kemungkinan besar ikut turun, dan itu bukan karena perusahaannya
bangkrut atau apa, tapi memang karena pasarnya sedang terkoreksi saja. Dengan
kata lain, saham anda turun bukan karena ada masalah di internal perusahaan, melainkan
karena faktor eksternal berupa
koreksi pasar.
Nah! Untuk kurs
Rupiah juga sama begitu: Dalam kondisi ekonomi yang aman terkendali maka Rupiah bukan berarti pasti akan stabil, melainkan bisa tetap turun karena faktor-faktor eksternal yang tidak terlalu berhubungan dengan fundamental makroekonomi. Contohnya
ya di tahun 2008, dimana Rupiah ketika itu jeblok bukan karena ekonomi nasional
lagi ada problem, tapi lebih karena kekhawatiran bahwa krisis subprime mortgage
yang ketika itu terjadi di AS akan meluas termasuk ke Indonesia. Buktinya
ketika kekhawatiran terkait krisis di AS itu mereda dengan
sendirinya di tahun 2009, maka seketika itu pula Rupiah perkasa lagi, hingga sempat
tembus dibawah 9,000 pada tahun 2011.
Sementara untuk
tahun 2018 ini, maka terdapat setidaknya tiga
faktor yang bikin Rupiah loyo. Pertama, kondisi ekonomi AS, seperti yang sudah
kita
bahas disini, sekarang ini lagi bagus-bagusnya, dan itu menyebabkan USD
menguat terhadap banyak mata uang lain termasuk Rupiah (jadi dalam hal ini USD
lah yang menguat, bukan Rupiah yang melemah). Kedua, harga minyak naik hingga
terakhir sudah tembus USD 70 per barel, dan ini otomatis menaikkan nilai impor
Indonesia, dan Rupiah kena imbasnya karena kita jadi butuh banyak Dollar
buat beli minyak. Dan ketiga, anda mungkin memperhatikan bahwa sudah setahunan
terakhir ini investor asing terus keluar dari bursa saham Indonesia, demikian
pula mereka banyak keluar dari obligasi, surat utang negara dll, dan itu praktis
menekan Rupiah, karena para investor asing ini banyak menukar Rupiah mereka
dengan Dollar. Penulis sampai sekarang masih belum mengerti, apa yang bikin
mereka keluar ramai-ramai (ada banyak teori soal ini, tapi
semuanya hanya sebatas teori yang belum bisa dibuktikan), tapi yang jelas
inilah yang bikin Rupiah turun.
Kabar baiknya, meski
penulis belum tahu seberapa lama kondisi ekonomi AS dan tekanan outflow asing
akan berdampak terhadap Rupiah, tapi terkait naiknya harga minyak, maka bisa
penulis katakan bahwa harga minyak saat
ini sudah cukup tinggi, dan harusnya gak akan sampai balik lagi ke level
USD 100-an per barel seperti sebelum tahun 2016 lalu (penjelasannya baca
lagi disini), dan bahkan kenaikan minyak ini juga sudah kita prediksi
sebelumnya (baca lagi prediksinya
disini, intinya terkait IPO Aramco). Jika proyeksi ini benar adanya, maka
posisi Rupiah saat ini sudah cukup
rendah, dimana kecuali kedepannya nanti ada peristiwa force majeure tertentu,
maka kita tidak akan melihat Rupiah turun sampai ke level seperti di tahun 2015
lalu.
Dampak Kenaikan BI
Rate?
Kalau anda teliti,
maka ulasan diatas sekaligus menjelaskan kenapa, berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya, Pemerintah sampai sekarang terkesan seperti cuek saja terhadap
pelemahan Rupiah ini. Pada tahun 2008, setelah Rupiah anjlok ke 12,000-an, Pemerintah ketika itu meluncurkan paket
kebijakan ekonomi termasuk menyelamatkan Bank
Century yang bermasalah, karena jika bank tersebut dibiarkan kolaps maka
dikhawatirkan akan berdampak sistemik, karena ketika itu psikologis market
sedang jelek-jeleknya seiring dengan hancurnya IHSG. Pada tahun
2013, tepatnya tanggal 23 Agustus 2013, Pemerintah juga meluncurkan ‘paket
kebijakan penyelamatan ekonomi’ setelah Rupiah ketika itu terjun bebas ke dari
9,000-an ke 11,000-an (baca lagi ceritanya
disini). Dan pada tahun 2015, tepatnya tanggal 9 September 2015 setelah Rupiah sempat tembus 15,000, Pemerintah
meluncurkan ‘Paket kebijakan ekonomi Jilid 1’, yang kemudian berlanjut pada
paket-paket kebijakan selanjutnya hingga terakhir Jilid 16, yang diluncurkan pada Agustus 2017 lalu (info lengkapnya
boleh gogling aja, kepanjangan kalo ditulis disini).
Tapi setelah paket
kebijakan ekonomi jilid 16 tersebut, sampai sekarang belum ada paket kebijakan
lagi. Kalaupun ada kebijakan, maka itu adalah keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan BI 7-day Rate, atau disingkat BI
Rate, dari sebelumnya 4.25% menjadi sekarang 5.25%, dan tujuannya sangat
jelas: Untuk membuat tingkat suku bunga atau yield di Indonesia kembali tampak menarik di mata investor asing, sehingga harapannya mereka kembali masuk
kesini, atau minimal gak keluar lebih lanjut. Dan jika itulah yang terjadi,
maka Rupiah juga diharapkan akan menguat kembali.
Namun disisi lain,
kenaikan BI Rate ini justru dikhawatirkan akan menurunkan kinerja sektor perbankan,
perusahaan pembiayaan, hingga properti. Karena secara teori, kalau bunga bank
naik maka omzet penyaluran kredit bank juga akan turun, demikian pula orang
yang beli mobil atau rumah pake kredit KPR akan berkurang. Tapi, okay, biar
kita luruskan semuanya disini.
Pertama, BI sebagai
otoritas moneter Indonesia memiliki goal untuk 1. Menjaga nilai tukar
Rupiah, 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan 3. Menekan inflasi. Jadi entah
itu BI menaikkan atau menurunkan BI Rate, maka seperti yang pernah kita bahas
disini (sekali lagi, buat yang belum mengerti cara kerja BI Rate, coba baca
dulu), harapannya adalah itu akan berdampak
positif terhadap tiga poin tujuan diatas. Yep, jadi pihak BI tidak akan menaikkan atau
menurunkan BI Rate dalam rangka menjaga
nilai tukar Rupiah, jika itu disisi lain menyebabkan perlambatan pertumbuhan
ekonomi, atau menaikkan inflasi ke level yang berbahaya. Tapi seperti yang kita
ketahui, pertumbuhan GDP sekarang ini stabil di level 5%, sementara inflasi
juga cukup rendah di level 3%, jadi sangat reasonable jika BI Rate
kemudian dinaikkan. Thus, meski bunga bank akan naik karena naiknya BI
Rate ini, tapi selama kegiatan ekonomi masih berjalan lancar, maka kenaikan suku bunga tidak
akan sampai menurunkan omzet kredit bank, sehingga kinerja mereka tidak akan
terganggu. Lain ceritanya jika BI Rate ini dinaikkan ketika ekonomi
sedang lesu-lesunya seperti tahun 2015 lalu, maka itu artinya wassalam.
Kedua, seiring
dengan turunnya inflasi sejak tahun 2015, maka BI Rate juga cenderung turun
dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai level 4.25%, yang merupakan level terendah dalam sejarah (antara
tahun 2005 hingga 2018, BI Rate rata-rata berada di level 7 – 8%). Maksud penulis adalah, yep, kalau BI Rate dinaikkan ke
level yang terlalu tinggi, maka biar
gimana itu akan ada dampak negatifnya terhadap perekonomian, tapi faktanya
angka BI Rate yang 5.25% sekarang ini terbilang masih rendah, dan suku bunga KPR, KUR juga masih berada di level yang
lebih rendah dibanding 2 – 3 tahun lalu. Jadi kalau BI Rate nanti naik lagi
sampai ke level seperti di tahun 2015 lalu, maka barulah kita perlu waspada. Tapi
karena kenaikan BI Rate sejauh ini hanya bertujuan untuk ‘merayu’ asing agar
masuk lagi kesini, dan bukan karena ekonomi kita ada problem, maka penulis kira
posisi BI Rate saat ini sudah cukup tinggi, dan tidak akan dinaikkan lebih lanjut
kecuali jika nanti terjadi peristiwa penting tertentu.
Anyway, kata kuncinya
disini adalah, jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap perekonomian maka Pemerintah
akan segera bertindak, termasuk BEI hingga OJK juga akan ‘do something’ jika
penurunan IHSG sudah kelewat dalem, contohnya ketika terjadi panic selling di tahun 2015 lalu, tapi faktanya sampai sekarang belum ada
tindakan khusus apapun. Sehingga bisa dikatakan bahwa kondisi market, atau
setidaknya di mata para pejabat berwenang yang sarat pengetahuan serta
pengalaman ini (kecuali anda punya sederet gelar seperti Tuan Doktor Profesor Patrick,
maka anda tidak bisa melamar jadi komisaris di OJK), masih aman terkendali. Hanya
memang, diluar cerita pelemahan Rupiah serta BI Rate ini maka diluar sana masih
banyak isu-isu negatif terkait perang
dagang dll, yang belum kita bahas disini. Tapi berhubung tulisan ini sudah
cukup panjang (dan mungkin anda juga sudah puyeng bacanya), maka soal itu kita
bahas lain waktu.
Ebook Kumpulan Analisis 30 Saham Pilihan ('Ebook Kuartalan') edisi Kuartal II 2018 akan terbit hari Rabu, 8 Agustus 2018. Anda bisa memperolehnya dengan cara preorder disini.
Follow/lihat foto-foto penulis di Instagram, klik 'View on Instagram' dibawah ini:

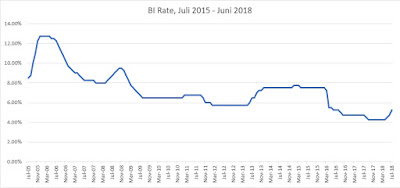







Komentar
Mohon penjelasannya. Trmkasih
Saat ini suku bunga acuan/policy rate itu BI 7-day Reverse Repo Rate. Ya emang kepanjangan sih namanya.
Menurut saya karena The Fed menaikkan suku bunga, Pak. Kalau US yang notabene negara aman suku bunga misal 3% dan Indonesia negara berkembang (yang relatif lebih risky) juga 3%, tentu orang akan memilih ke negara yang aman dengan hasil yang sama. Bahkan kalau lebih rendah sedikit pun, itu seperti "gapapa mahalan dikit tapi bagus".
Kayaknya sih yg dimaksud KRAS,, cuman nenunggu analisanya pak teguh!
USD yang beredar ditarik teratur oleh the fed, dan dalam tiga tahun ini kecepatannya ditingkatkan, terjadi overdemand terhadap USD, itu yang jadi penyebab lira turki, peso argentina, rupiah dan sederet mata uang lain tiarap lawan USD.
coba tengok lagi great depression 1929, posisi kita sekarang sangat mirip, bedanya jika dulu peran kreditur, produsen, konsumen dipegang US, sekarang beberapa peran sudah diambil Cina, Jepang dan sederet negara penghasil komoditas, itu artinya, skala krisis kali ini akan lebih besar dari great depression 1929. jika pasca 1929 terjadi PD II, apa kabar kita nanti? entah lah, yang jelas Iran Cina UE dan sederet wilayah lain udah mulai panas
Subsidi bbm
Adalah salah satu sumber pelemahan rupiah